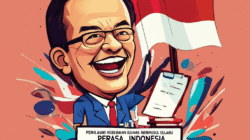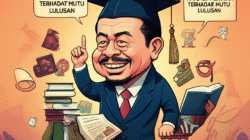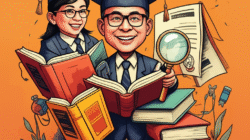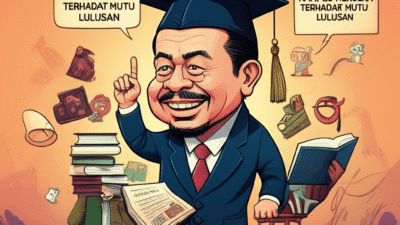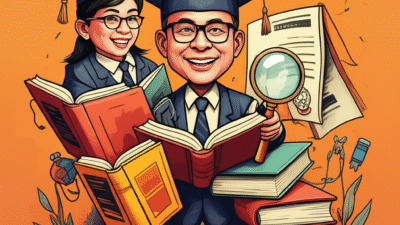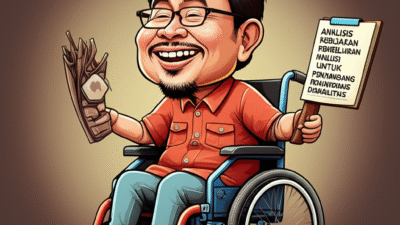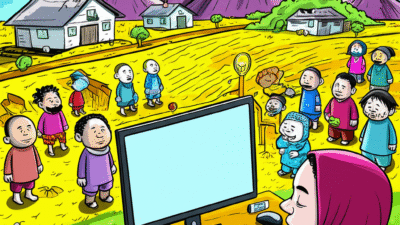Politik Agraria: Perebutan Tanah, Keadilan, dan Masa Depan Bangsa
Pendahuluan
Tanah bukan sekadar hamparan fisik, melainkan jantung kehidupan, sumber penghidupan, identitas budaya, dan penentu keberlanjutan sebuah peradaban. Oleh karena itu, hubungan manusia dengan tanah senantiasa menjadi medan kompleks yang melibatkan dimensi ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan. Dalam konteks ini, "politik agraria" muncul sebagai arena perebutan kekuasaan, sumber daya, dan keadilan dalam pengelolaan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam lainnya. Ia adalah cerminan dari bagaimana suatu negara mendistribusikan kekayaan alamnya, melindungi hak-hak rakyatnya, dan merancang masa depan pangan serta kesejahteraan warganya.
Di Indonesia, sebagai negara agraris dan maritim dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, politik agraria memiliki relevansi yang sangat mendalam. Sejarah bangsa ini diwarnai oleh pergulatan agraria, mulai dari era kolonialisme yang merampas tanah rakyat, hingga perjuangan kemerdekaan yang salah satunya mengusung cita-cita keadilan agraria, dan dinamika pasca-kemerdekaan yang kerap diwarnai konflik dan ketimpangan. Artikel ini akan mengupas tuntas politik agraria di Indonesia, meliputi sejarah, dimensi-dimensi krusial, tantangan kontemporer, serta prospek menuju keadilan dan keberlanjutan.
Sejarah Singkat Politik Agraria di Indonesia: Dari Kolonialisme hingga Reformasi Agraria yang Mandek
Untuk memahami politik agraria di Indonesia saat ini, kita harus menengok ke belakang. Jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, sistem penguasaan tanah di Nusantara umumnya bersifat komunal atau berdasarkan hak ulayat masyarakat adat, di mana tanah dipandang sebagai milik bersama dan dimanfaatkan untuk kepentingan komunitas. Meskipun terdapat struktur feodal, kepemilikan individu atas tanah dalam skala besar relatif jarang.
Kedatangan kolonialisme, terutama Belanda, mengubah lanskap agraria secara fundamental. Pemerintah kolonial memperkenalkan sistem kepemilikan tanah Barat (hak eigendom, erfpacht, opstal) yang mengabaikan atau bahkan menghapus hak-hak adat. Tanah-tanah produktif dirampas untuk perkebunan skala besar (tebu, kopi, teh, karet) demi kepentingan ekonomi kolonial. Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) 1870 dan Peraturan Gula (Suiker Wet) 1870 menjadi instrumen hukum yang melegitimasi penguasaan tanah oleh modal swasta dan pemerintah kolonial, menciptakan jurang pemisah antara petani pribumi yang kehilangan tanah dengan perusahaan-perusahaan besar. Inilah awal mula ketimpangan struktural dalam penguasaan tanah yang masih terasa hingga kini.
Pasca-kemerdekaan, semangat untuk mengoreksi ketimpangan kolonial sangat kuat. Puncaknya adalah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. UUPA 1960 adalah mahakarya legislasi yang progresif, berlandaskan Pancasila, yang secara tegas mencabut hukum agraria kolonial dan menetapkan prinsip "hak menguasai negara" atas tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. UUPA 1960 juga mengamanatkan pelaksanaan reforma agraria yang sejati, yaitu penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang adil dan merata. Tujuannya adalah menghapuskan feodalisme agraria, mencegah monopoli tanah, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Namun, implementasi UUPA 1960 tidak berjalan mulus. Gerakan reforma agraria yang digulirkan pada era Orde Lama terhenti pasca-peristiwa 1965. Rezim Orde Baru di bawah Soeharto, meskipun secara retoris tidak mencabut UUPA 1960, namun dalam praktiknya lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi yang berbasis pada investasi skala besar, industrialisasi, dan eksploitasi sumber daya alam. Kebijakan "revolusi hijau" memang meningkatkan produksi pangan, tetapi juga memperlebar kesenjangan agraria, mendorong penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara masif, serta meminggirkan petani gurem. Hak-hak masyarakat adat semakin tergerus oleh izin-izin konsesi kehutanan, pertambangan, dan perkebunan sawit yang dikeluarkan secara masif, seringkali tanpa persetujuan masyarakat setempat, memicu ribuan konflik agraria.
Dimensi-Dimensi Kritis dalam Politik Agraria Kontemporer
Politik agraria di Indonesia hari ini melibatkan setidaknya lima dimensi krusial yang saling terkait:
-
Ketimpangan Penguasaan dan Distribusi Tanah:
Ini adalah akar masalah utama. Data menunjukkan bahwa sebagian kecil elite menguasai sebagian besar lahan produktif di Indonesia, sementara jutaan petani gurem dan buruh tani tidak memiliki atau hanya memiliki lahan yang sangat sempit. Konsentrasi kepemilikan tanah pada segelintir korporasi besar, terutama di sektor perkebunan dan pertambangan, telah menciptakan ketimpangan struktural yang parah. Akibatnya, jutaan rumah tangga petani hidup dalam kemiskinan dan rentan terhadap penggusuran. Konflik agraria, yang melibatkan sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan atau pemerintah, terus meningkat setiap tahunnya, seringkali berakhir dengan kekerasan dan kriminalisasi petani. -
Keadilan Sosial dan Hak Asasi Manusia:
Politik agraria adalah juga tentang keadilan sosial. Petani, masyarakat adat, nelayan tradisional, dan masyarakat pesisir adalah kelompok-kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif dari kebijakan agraria yang tidak adil. Perampasan tanah, penggusuran paksa, kriminalisasi aktivis agraria, dan hilangnya mata pencarian adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka menjadi isu sentral, mengingat peran penting tanah adat dalam menjaga kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan. -
Ketahanan Pangan dan Pembangunan Ekonomi:
Tanah adalah basis produksi pangan. Politik agraria yang berpihak pada petani kecil dan menengah akan memperkuat ketahanan pangan nasional. Sebaliknya, konversi lahan pertanian produktif menjadi non-pertanian (perumahan, industri, infrastruktur) mengancam ketersediaan pangan di masa depan. Perdebatan antara "ketahanan pangan" (food security) yang sering diartikan sebagai kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan pangan melalui produksi domestik atau impor, dengan "kedaulatan pangan" (food sovereignty) yang menekankan hak masyarakat untuk menentukan sistem pangan mereka sendiri, menunjukkan kompleksitas isu ini. Ketergantungan pada impor pangan dan dominasi korporasi multinasional dalam rantai pasok pangan juga menjadi isu krusial yang mengancam kemandirian bangsa. -
Keberlanjutan Lingkungan dan Perubahan Iklim:
Politik agraria memiliki dampak langsung terhadap lingkungan. Ekspansi perkebunan monokultur (terutama sawit), pertambangan, dan industri ekstraktif telah menyebabkan deforestasi besar-besaran, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi tanah, polusi air, dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Perubahan iklim, pada gilirannya, juga berdampak pada sektor pertanian melalui kekeringan, banjir, dan pergeseran musim tanam, yang memperparah kerentanan petani. Oleh karena itu, politik agraria harus berorientasi pada praktik-praktik pertanian berkelanjutan (agroekologi), restorasi ekosistem, dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. -
Kerangka Hukum dan Kelembagaan:
Meskipun UUPA 1960 masih berlaku, implementasinya kerap berbenturan dengan berbagai undang-undang sektoral lainnya (UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Perkebunan, UU Penataan Ruang) yang seringkali lebih berpihak pada kepentingan investasi dan pembangunan infrastruktur skala besar. Tumpang tindih regulasi, lemahnya penegakan hukum, dan korupsi di birokrasi pertanahan memperparah konflik agraria. Diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan kelembagaan pertanahan yang independen dan berpihak pada keadilan agraria.
Tantangan Kontemporer dan Dinamika Global
Politik agraria di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat dinamika global. Arus investasi asing yang masif ke sektor sumber daya alam, tuntutan pasar global terhadap komoditas pertanian, dan perjanjian perdagangan bebas, semuanya memberikan tekanan pada penguasaan tanah dan hak-hak masyarakat lokal. Megaproyek infrastruktur nasional juga semakin mempercepat konversi lahan dan memicu penggusuran.
Perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi sektor pertanian, yang menuntut adaptasi dan mitigasi yang serius. Sementara itu, pertumbuhan populasi dan urbanisasi terus menekan lahan pertanian, mendorong fragmentasi lahan dan mengurangi minat generasi muda untuk bertani. Revolusi industri 4.0 dan digitalisasi juga mulai merambah sektor pertanian, membawa potensi efisiensi namun juga risiko disrupsi bagi petani kecil jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang inklusif.
Menuju Politik Agraria yang Adil dan Berkelanjutan
Mewujudkan politik agraria yang adil dan berkelanjutan adalah prasyarat bagi kemakmuran dan stabilitas bangsa. Beberapa langkah kunci yang harus ditempuh meliputi:
- Reforma Agraria Sejati dan Komprehensif: Ini bukan hanya tentang redistribusi tanah, tetapi juga tentang penguatan hak-hak petani, akses terhadap modal, teknologi, pasar, dan infrastruktur. Reforma agraria harus menjadi prioritas nasional yang serius, dengan target yang jelas dan mekanisme penyelesaian konflik yang adil.
- Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat: Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat adalah langkah krusial untuk melindungi hak-hak mereka atas tanah ulayat dan sumber daya alam, serta mencegah konflik di kemudian hari.
- Pengendalian Konversi Lahan dan Perlindungan Lahan Pertanian: Kebijakan yang ketat diperlukan untuk mencegah konversi lahan pertanian produktif dan memastikan ketersediaan lahan untuk produksi pangan di masa depan.
- Mendorong Pertanian Berkelanjutan: Transisi menuju praktik pertanian agroekologi, yang ramah lingkungan dan berbasis pada kearifan lokal, harus didukung penuh melalui insentif, penelitian, dan penyuluhan.
- Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum: Reformasi birokrasi pertanahan, pemberantasan korupsi, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perampasan tanah dan pelanggar hak asasi manusia di sektor agraria adalah mutlak.
- Partisipasi Bermakna: Kebijakan agraria harus dirumuskan dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, terutama petani, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil.
Kesimpulan
Politik agraria adalah cerminan dari bagaimana suatu bangsa menghargai tanahnya dan memperlakukan rakyatnya. Di Indonesia, sejarah telah menunjukkan bahwa ketimpangan agraria adalah sumber konflik dan ketidakadilan yang berkelanjutan. Meskipun UUPA 1960 memberikan landasan yang kuat untuk keadilan agraria, implementasinya masih jauh dari harapan.
Tantangan di masa depan semakin besar, mulai dari tekanan globalisasi, perubahan iklim, hingga dinamika demografi. Oleh karena itu, komitmen politik yang kuat, keberanian untuk menata ulang struktur penguasaan tanah, serta keberpihakan yang nyata kepada rakyat kecil adalah kunci untuk mewujudkan politik agraria yang adil dan berkelanjutan. Dengan begitu, tanah tidak hanya menjadi sumber konflik, melainkan fondasi bagi kesejahteraan, keadilan sosial, dan masa depan bangsa yang mandiri dan berdaulat.